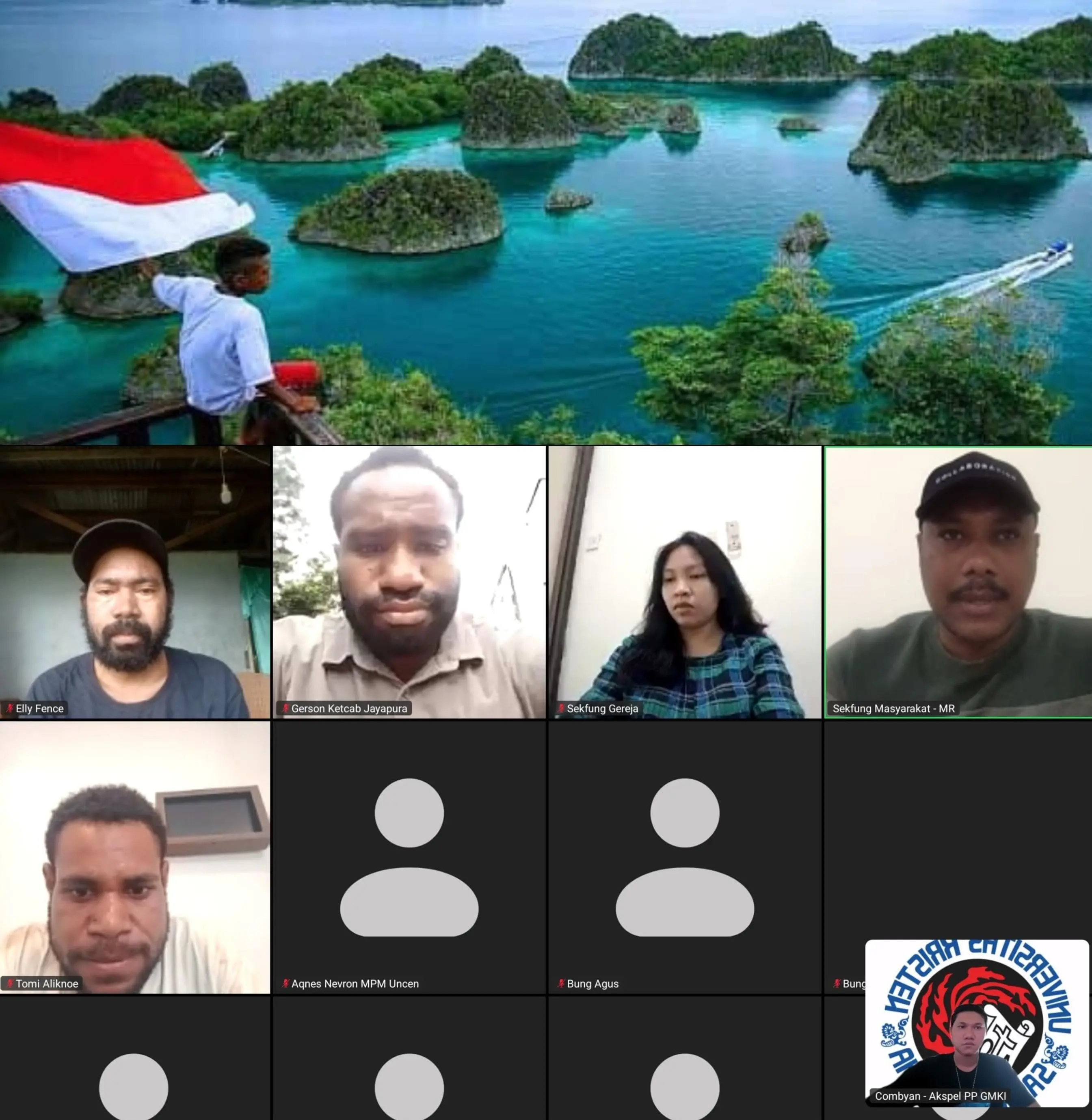Oleh: Irhas Abdul Hadi (Ketua Umum HMI Cabang Ciputat)
Gelombang demonstrasi pada 25–28 Agustus 2025 menandai babak baru pergulatan politik Indonesia. Apa yang dimulai dari sebuah insiden sederhana seorang pengemudi ojek online yang ditabrak aparat berubah menjadi kerusuhan nasional dengan korban jiwa, ribuan luka-luka, dan tuntutan yang menggema di jalanan.
Namun, alih-alih meredam dengan empati, Presiden Prabowo Subianto justru mengambil langkah mengejutkan: menaikkan pangkat aparat yang terlibat, sementara korban jiwa belum ia kunjungi, dan tuntutan massa yang meminta pergantian Kapolri diabaikan. Sebuah keputusan yang mungkin logis dalam logika militer, tetapi berbahaya dalam logika politik.
Dari Insiden ke Ledakan: Butterfly Effect Aksi Massa
Dalam teori sosial, butterfly effect menggambarkan bagaimana peristiwa kecil dapat memicu badai besar. Insiden penabrakan itu hanyalah pemicu, bukan penyebab utama. Akumulasi kekecewaan publik terhadap korupsi, sentralisasi fiskal (turunnya transfer pusat-daerah dari Rp900 triliun di 2025 menjadi Rp600 triliun di 2026) bisa menjadi sebab, perilku pejabat publik yang nirempati bertindak tanpa memikirkan kondisi masyarakat, serta gaya kepemimpinan yang dianggap militeristik, telah lama mengendap.
Fenomena ini bukan khas Indonesia. Dunia sudah melihat pola serupa:
- Tunisia 2010, ketika Mohamed Bouazizi membakar diri, memicu Arab Spring.
- Iran 1979, protes harga bahan bakar berubah menjadi revolusi besar.
- Indonesia 1998, penembakan mahasiswa Trisakti menjadi detonator jatuhnya Orde Baru.
Polanya sama: insiden kecil menjadi simbol ketidakadilan struktural yang tak tertahankan.
Antara Soliditas Aparat dan Empati Publik
Langkah PS menaikkan pangkat aparat jelas dimaksudkan untuk menjaga moral dan soliditas TNI–Polri. Ia mungkin teringat 1998, ketika keretakan aparat mempercepat runtuhnya rezim Soeharto. Namun, pilihan ini berhadapan langsung dengan tuntutan publik.
Max Weber pernah menegaskan, ada tiga sumber legitimasi kekuasaan: tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Di era modern, legitimasi aparat tidak cukup. Rakyat menuntut moralitas dan akuntabilitas.
Sejarah memberi banyak pelajaran:
- Uni Soviet 1991, aparat tetap kuat, tetapi rezim runtuh karena kehilangan legitimasi rakyat.
- Mesir 2011, Presiden Mubarak bertahan dengan polisi dan tentara, tapi jatuh hanya dalam 18 hari karena publik kehilangan kepercayaan.
Pesannya jelas: kekuasaan yang hanya bertumpu pada kekuatan senjata akan rapuh tanpa fondasi legitimasi rakyat.
Indonesia di Persimpangan Sejarah
Aksi sporadis tempo hari memang belum punya konsensus tuntutan yang kuat. Massa terpecah: ada yang menuntut perombakan kabinet, ada yang menolak sentralisasi anggaran, ada pula yang menuntut reformasi sistem politik. Namun satu benang merahnya sama: kekecewaan terhadap elite yang dianggap abai pada rakyat.
Di sisi lain, elite politik dan oligarki yang tersingkir ikut menunggangi momentum. Sejarah Indonesia sudah akrab dengan pola ini: mahasiswa dan rakyat turun ke jalan dengan idealisme, sementara elite di belakang layar menjadikannya alat tawar-menawar kekuasaan.
Kondisi ini mirip dengan Prancis pra-Revolusi 1789. Rakyat hanya meminta harga roti yang terjangkau, tetapi istana sibuk menjaga privilese bangsawan. Hasilnya, badai revolusi menghantam tanpa ampun.
Jalan Keluar: Belajar dari Critical Junctures
Dalam teori politik, ada istilah critical juncture momen kritis yang menentukan arah sejarah bangsa. 25–28 Agustus 2025 adalah salah satunya.
PS punya dua pilihan:
- Tetap pro-aparat, anti-empati → mungkin menjaga soliditas jangka pendek, tapi berisiko kehilangan legitimasi rakyat, mengulang kesalahan rezim-rezim yang tumbang.
- Pivot ke rakyat, pro-reformasi → dengan merangkul civil society, merombak kabinet, dan memperbaiki kebijakan fiskal pusat-daerah. Berat, tapi hanya itu cara menjaga legitimasi jangka panjang.
Sebagai penutup, bahwa sejarah dunia, dari Revolusi Prancis, kejatuhan Uni Soviet, Arab Spring, hingga Reformasi Indonesia, memberi pelajaran serupa:
Negara yang mengabaikan tanda-tanda kecil, dan lebih memilih kekuatan aparat ketimbang legitimasi rakyat, akan berhadapan dengan badai sejarah yang tak bisa dibendung.
Prabowo Subianto kini berada di titik krusial. Ia bisa menjadi pemimpin yang menulis bab baru dengan keberanian politik, atau hanya catatan lain dalam daftar panjang pemimpin yang tumbang karena gagal membaca tanda zaman.
Opini ini ditulis sebagai refleksi, bukan sekadar kritik. Karena dalam setiap peristiwa, sejarah selalu memberi tanda. Dan tanda itu, hari ini, sudah sangat jelas.
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
Top Story
Ikuti kami