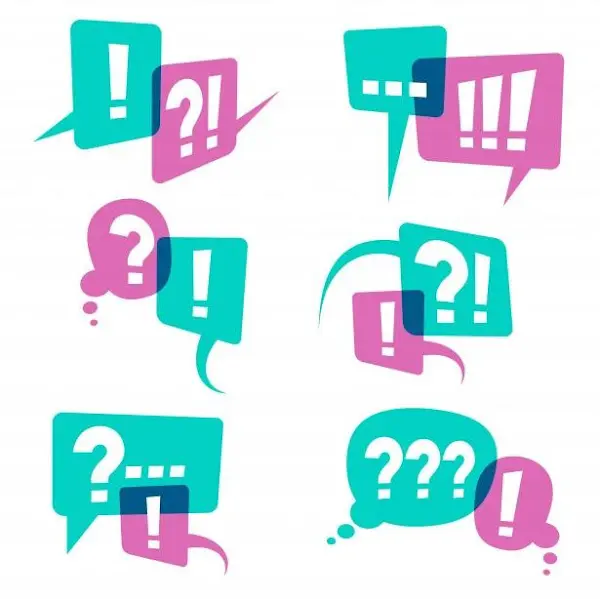Oleh: Fachrur Rozi Al Fahdli
Indonesia dibangun di atas fondasi persatuan dalam keberagaman. Demokrasi kita, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Ketentuan ini menjadi fondasi utama demokrasi konstitusional di Indonesia yang menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana yang memunculkan kegelisahan konstitusional, yaitu dorongan agar hak untuk dipilih dalam kontestasi politik terutama di daerah hanya diberikan kepada individu yang berasal dari daerah tersebut atau yang disebut sebagai "Putra Daerah".
Praktik ini didorong oleh sentimen lokalitas, semangat kultural, dan keinginan menjaga jati diri daerah, namun pada saat yang sama berpotensi besar melanggar prinsip demokrasi yang inklusif, adil, dan setara. Latar belakang dari munculnya gagasan ini memang tidak terlepas dari sejarah panjang keterpinggiran daerah-daerah tertentu, kekecewaan terhadap elit nasional, serta romantisasi terhadap kepemimpinan lokal yang dianggap lebih memahami kultur masyarakat setempat. Akan tetapi, ketika keterikatan geografis dijadikan syarat legal untuk mendiskualifikasi hak konstitusional warga negara Indonesia dari luar daerah tersebut, maka demokrasi telah berbelok dari jalur universalitasnya.
Secara normatif, ide eksklusivitas daerah dalam demokrasi elektoral bertentangan secara langsung dengan semangat UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,” serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan larangan segala bentuk diskriminasi. Hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak politik yang dilindungi konstitusi.
Oleh karena itu, membatasi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya karena ia bukan "asli daerah" merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip kesetaraan warga negara. Hukum positif Indonesia juga tidak mengenal pembatasan tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencantumkan keharusan bahwa calon kepala daerah atau legislatif berasal dari daerah yang sama.
Syarat pencalonan bersifat administratif (seperti usia, pendidikan, dan surat bebas pidana) serta dukungan politik yang sah. Eksklusivitas daerah dalam konteks demokrasi elektoral dapat dipahami sebagai pandangan yang menempatkan identitas kedaerahan sebagai tolok ukur utama kelayakan politik seseorang.
Dengan demikian, eksklusivitas berbasis daerah tidak hanya tidak memiliki dasar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum. Komitmen terhadap prinsip ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional. Indonesia sebagai negara pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah meratifikasi instrumen tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 25 ICCPR, ditegaskan bahwa: "Setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan, tanpa diskriminasi dan tanpa pembatasan yang tidak masuk akal: (a) untuk mengambil bagian dalam pengelolaan urusan publik, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (b) untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur." Pasal ini memperkuat bahwa hak untuk dipilih adalah bagian dari hak sipil yang tidak boleh dibatasi kecuali dengan alasan yang sah dan proporsional. Maka, membatasi pencalonan atas dasar asal-usul daerah bertentangan pula dengan standar hak asasi manusia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum nasional dan internasional telah memberikan landasan yang inklusif bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam ruang politik tanpa sekat kedaerahan. Salah satu contoh nyata yang pernah menjadi sorotan publik adalah polemik pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat mencalonkan diri, Ahok menghadapi resistensi dari kelompok tertentu yang mempermasalahkan latar belakang etnis dan kedaerahannya, meskipun secara hukum ia memenuhi semua syarat administratif sebagai calon kepala daerah.
Penolakan itu tidak didasarkan pada ketidaksesuaian syarat legal, melainkan pada identitas non-substantif: bukan “warga asli Jakarta” dan berasal dari etnis minoritas. Meski demikian, ia tetap lolos sebagai kandidat karena hukum tidak mengenal keharusan “Putra Daerah”. Kasus ini menjadi bukti kuat bahwa tekanan berbasis identitas lokal dapat menjadi bentuk eksklusivitas yang merongrong demokrasi, meskipun tidak tercantum secara formal dalam regulasi. Pada saat yang sama, ini memperlihatkan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga agar hak dipilih tidak diganggu oleh sentimen primordial yang tidak relevan dengan substansi kepemimpinan.
Komitmen terhadap prinsip non-diskriminasi ini juga tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas memperkuat jaminan atas hak politik setiap individu. Dalam Putusan MK No. 57/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan bahwa hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak asasi politik yang tidak dapat dibatasi secara diskriminatif kecuali karena alasan yang sah menurut hukum. Sementara dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menolak segala pembatasan yang bersifat eksklusif karena berpotensi menghilangkan hak politik warga negara hanya berdasarkan identitas personal yang tidak relevan secara substantif terhadap kualitas kepemimpinan.
Di sisi lain, dari perspektif teori hukum, gagasan eksklusivitas daerah bertentangan dengan prinsip deliberatif democracy ala Jürgen Habermas yang menekankan bahwa politik harus bersifat inklusif, rasional, dan terbuka bagi semua warga negara. Dalam pandangan ini, keterlibatan dalam proses demokrasi seharusnya diukur dari kualitas ide, kapabilitas kepemimpinan, serta integritas moral, bukan dari latar geografis atau darah keturunan.
Secara sosiologis, eksklusivitas daerah berisiko mendorong segregasi sosial dan memperkuat politik identitas yang destruktif. Emile Durkheim, dalam teori solidaritas organik, menyatakan bahwa masyarakat modern hanya dapat hidup harmonis jika dibangun atas dasar diferensiasi dan integrasi antar kelompok.
Menutup akses politik hanya untuk "orang asli daerah" sama dengan membatasi ruang sosial bagi warga negara Indonesia dari luar daerah tersebut untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. Ini bukan hanya bertentangan dengan cita-cita integrasi nasional, tetapi juga mempersempit ruang meritokrasi dan menjauhkan rakyat dari pilihan terbaik dalam kontestasi demokratis. Jika eksklusivitas ini dilegalkan, maka dalam jangka panjang akan terjadi pengkotakan dalam sistem politik nasional, di mana kualitas pemimpin dikalahkan oleh asal muasal, bukan oleh kompetensi dan gagasan.
Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk dipilih tanpa diskriminasi berbasis asal daerah. Solusi yang tepat untuk menjawab keresahan kultural daerah bukanlah dengan membatasi hak politik warga negara Indonesia dari luar daerah tersebut, melainkan dengan memperkuat pendidikan politik lokal, membuka akses yang adil terhadap informasi publik, serta mendorong partai politik untuk melakukan rekrutmen yang berbasis meritokrasi dan keterwakilan substansial.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mempertegas bahwa hak untuk dipilih adalah hak semua warga negara, dan setiap bentuk tekanan sosial yang mengarah pada diskriminasi politik harus ditepis dengan ketegasan hukum. Masyarakat sipil, akademisi, dan media juga memiliki peran penting dalam mendidik publik bahwa pemimpin yang baik tidak lahir dari identitas geografis semata, melainkan dari kualitas visi, integritas, dan dedikasi terhadap kepentingan publik.
Demokrasi sejati bukan dibangun dari batas-batas kultural, melainkan dari kebebasan seluruh rakyat untuk mengabdi. Setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke, memiliki hak yang sama untuk memimpin tanpa harus menegaskan asal-muasal. Sebab dalam negara hukum, yang diukur bukan dari mana seseorang berasal, tetapi sejauh mana ia bisa membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
Top Story
Ikuti kami